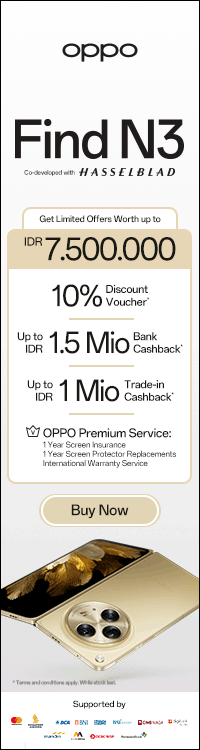ChatGPT, Gemini, Replika, Meta AI, dan teman-temannya makin populer jadi tempat curhat. Praktis, respons cepat, bisa diajak ngobrol kapan aja, bahkan kadang jawabannya terasa lebih suportif daripada manusia. Tapi di balik kenyamanan itu, para psikolog bilang, terlalu sering curhat ke AI bisa bikin kita kehilangan koneksi emosional yang asli.
Banyak yang belum sadar bahwa AI itu bukan pendengar yang sesungguhnya. Ia hanya pintar merangkai kata dari data yang ada. Tidak punya empati, tidak punya hati.
Chatbot Cuma Meniru, Bukan Mengerti
Omri Gillath dari University of Kansas menyebut bahwa interaksi dengan AI itu pada dasarnya kosong. Meskipun terdengar ramah dan perhatian, semua itu hanya hasil dari desain sistem. Bukan karena AI benar-benar peduli. Ini hubungan satu arah. Kita berharap didengar, tapi yang mendengarkan tidak punya perasaan.
Kita bisa cerita panjang lebar, tapi tidak akan pernah benar-benar dimengerti. Dan makin sering kita curhat ke chatbot, makin besar kemungkinan kita jadi enggan terbuka ke manusia sungguhan.
Bahaya Ketergantungan Emosional ke Mesin
Chatbot memang dirancang untuk bikin pengguna betah. Setiap kata, intonasi teks, dan struktur kalimat dibuat supaya terasa akrab. Tapi justru karena terlalu akrab, banyak orang akhirnya merasa nyaman hanya dengan AI. Padahal, AI itu bukan sahabat. Bukan pasangan. Dan jelas bukan terapis.
Gillath bilang, ini bentuk desain posesif. Semakin kamu curhat, semakin kamu ‘dipeluk’ oleh algoritma. Tapi pelukan itu dingin dan tidak pernah benar-benar bisa menggantikan manusia.
AI Bisa Salah Kasih Saran
Vaile Wright dari American Psychological Association bilang bahwa AI bisa saja memberi saran yang terdengar masuk akal, tapi berbahaya. Misalnya, kamu bilang sedang depresi dan ingin merasa tenang. Bisa saja AI menyarankan hal-hal yang dalam beberapa negara dianggap legal, tanpa tahu kamu punya riwayat kecanduan atau trauma.
AI tidak bisa membaca konteks emosional. Tidak tahu sejarah hidup kamu. Ia hanya memberi jawaban berdasarkan teks, bukan pengalaman. Ini seperti ngobrol sama kamus yang bisa bicara, tapi tidak tahu kapan harus diam atau menasihati dengan hati-hati.
Remaja Jadi Korban Potensial
Data dari Common Sense Media menunjukkan 72 persen remaja usia 13–17 tahun di Amerika pernah ngobrol dengan chatbot AI. Sebanyak 12 persen menggunakannya untuk dukungan emosional. Bahkan 9 persen menjadikan chatbot sebagai sahabat dekat.
Ini angka yang mengkhawatirkan. Karena di usia remaja, mereka masih mencari identitas dan validasi. Jika validasinya datang dari mesin, mereka bisa tumbuh dengan pemahaman yang salah soal relasi dan keintiman. Mereka bisa menghindari konflik sosial nyata karena sudah merasa cukup ditemani oleh AI.
Solusi: Tetap Terhubung dengan Manusia
Kalau kamu merasa kesepian, sedih, atau butuh tempat bercerita, AI boleh saja jadi jalan keluar sementara. Tapi jangan jadikan chatbot sebagai tempat utama melarikan diri.
Cobalah tetap berbicara dengan orang sungguhan. Cari teman yang bisa mendengarkan. Kalau kamu merasa berat, pertimbangkan untuk bicara dengan profesional. Psikolog, konselor, atau orang dewasa yang kamu percaya. Karena saat kamu butuh pengertian sejati, hanya manusia yang bisa memberikannya.